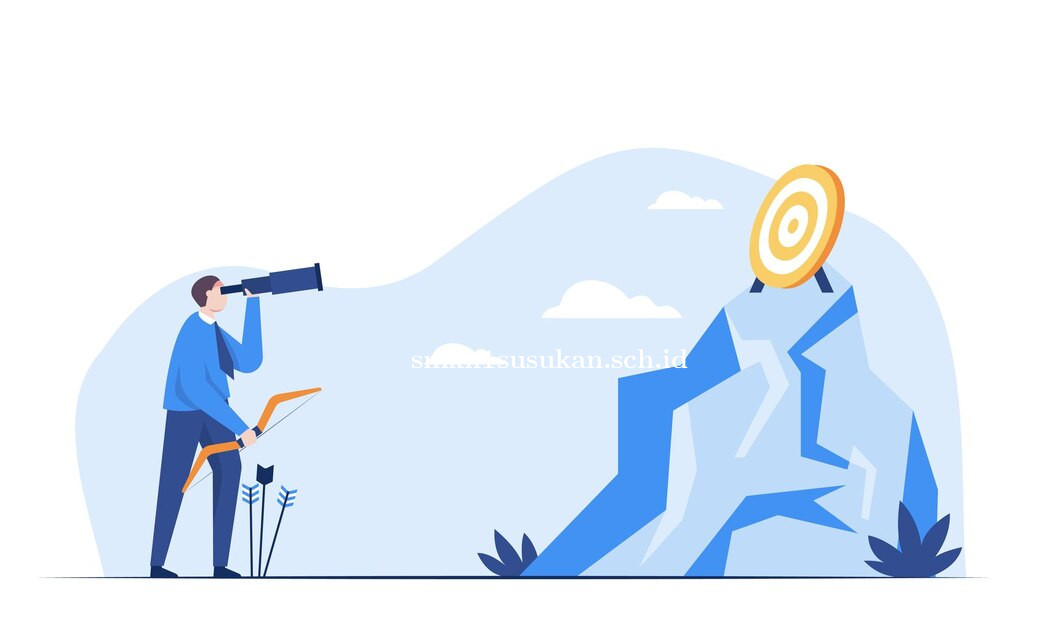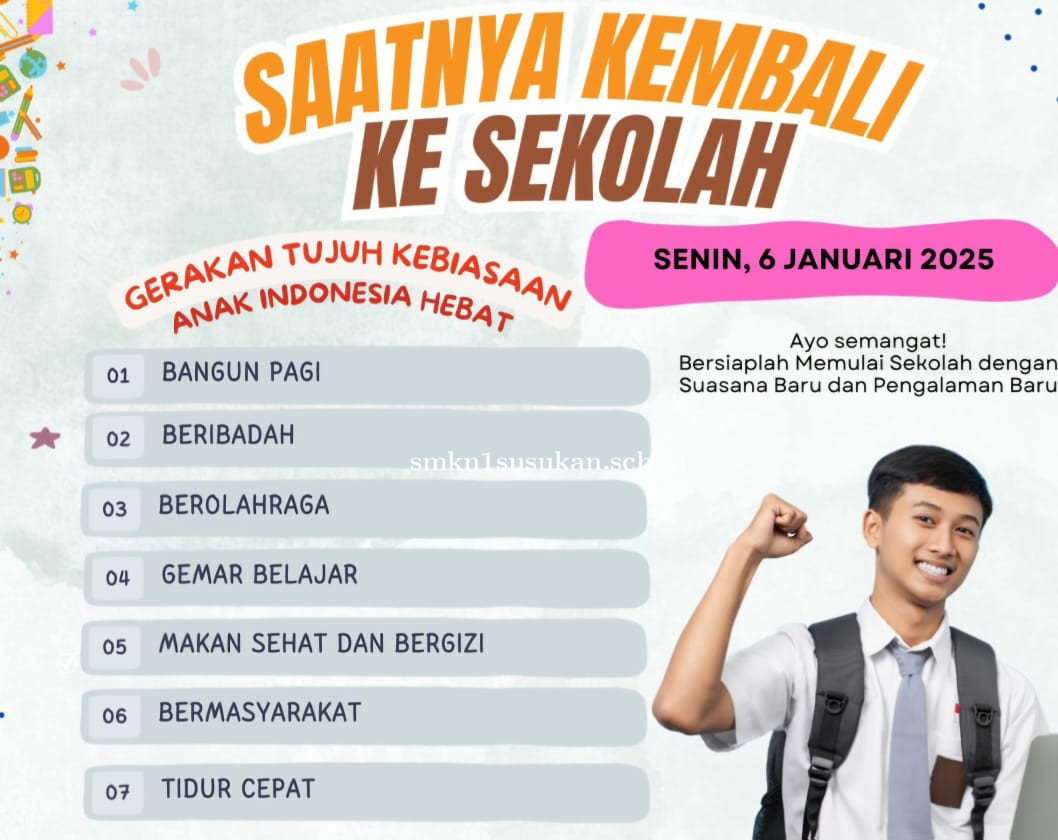Kegiatan PKL di DUDI/ Instansi
...- REKAPITULASI REALISASI SEMESTER 2
- SMK Negeri 1 Susukan Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H
- Kegiatan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah: Tingkatkan Kesadaran Hukum Murid SMK Negeri 1 Susukan
- KESEPAKATAN MURID SMK NEGERI 1 SUSUKAN TAHUN AJARAN 2025/2026
- RAPAT PLENO
- HARI ANAK NASIONAL
- REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP
- PARENTING
- APEL PELEPASAN SISWA/SISWI KELAS XII&XIII SMKN 1 SUSUKAN
- Pengumuman Kelulusan Tahun Ajaran 2024/2025
Semua Tidak Harus Sempurna
Sebuah Cerpen oleh Kutipan Rasa

Tempat kami tergolong tempat yang langka. Kenapa begitu? Karena tempat kami tak dapat dijangkau google maps, ditambah lagi kondisi jalan yang sangat rusak beserta arah yang berlika-liku, naik turun. Ada yang bilang “ enak sekali hidup di kampung! Udaranya segar, sepi dan damai.” Kebanyakan orang mungkin beranggapan seperti itu, tak masalah emang karena ada benarnya. Akan tetapi, tidak tahukah mereka bahwa kami yang di kampung juga tak se-enak itu, kami membutuhkan mental yang kuat dalam membawa kendaraan karena jalan yang rusak parah.
Kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai di pekotaan saat hendak membeli beberapa keperluan. Kami susah dalam mengakses internet. Kami harus ke sana ke mari mencari sinyal, tak jarang kami sampai naik pohon hanya demi mendapatkannya. Meskipun hal seperti ini sangat menyusahkan, tetapi kami tidak mempermasalahkannya karena memang setiap manusia sudah ditakdirkan hidup dimana, bukan?
“ Nak, kapan kamu mulai bisa bawa motor seperti, faida? Lihatlah dia! Baru belajar beberapa hari, sudah bisa bawa motor sendiri ke sekolah,” ujar ayahku, Rian. Aku hanya bisa menunduk, diam. Aku tak bisa menjawab pertanyaan ayah. Menjawab pun, ayah tak mungkin bisa mengerti perasaanku.
“ bukan Faida saja, tapi lihat Risti, Dian. Contoh tuh kayak mereka!” semakin keras saja ucapan ayah. Setelah itu ayah berjalan ke luar.
Aku masih menunduk, berjalan menuju kamar. Dududk di lantai, merenung. Mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Mengapa dulu aku mengalami kejadian itu, dan mereka tidak? Tak adil sekali. Aku ingin seperti mereka tapi ketakutanm ini lama lama membunuh mentalku. Aku hanya bisa menangis tanpa isakan. Mengapa dan mengapa? Andai mereka tahu, bahwa tak semudah ini berdamai dengan masa lalu, pahit.
Ayah selalu memaksaku untuk seperti mereka, tapi ayah tidak pernah membantuku keluaar dari sakit ini dan berdamai dengan luka. Aku juga ingin seperti mereka, tetapi kenapa susah sekali. Aku benci! Kenapa aku tidak bisa seperti mereka! Arghh. Sakit, hiks. Aku berdiri, membaringkan tubuh. Lebih baik aku tidur, aku harus siap dengan hari esok. Ah, membayangkan hari esok saja, terasa ada desiran aneh di dada, sakit.
Pagi hari, aku sedang bersiap siap ke sekolah. Ayah bertanya, lagi. “ berangkat sama siapa, Nin?” Oh, iya, adalah Anindia Rahma biasa dipanggil Nindi.
“Faida, Yah,” jawabku.
“Gak, mau nyoba bawa motor sendiri? Faida pasti bosen kamu nebeng terus,” tanya ayah, skak.
“Belum siap lagi, Yah. Harusnya ayah ngertiin aku.” Oke, aku coba memberanikan diri.
“Haha ngertiin kamu bilang? Ayah udah ngertiin kamu dari dulu. Ayah udah beliin kamu motor supaya kamu bisa latihan, tapi pas udah di beliin kamu malah gak belajar sama sekali.” Lagi dan lagi jawaban seoerti itu yang di berikan ayah.
Ya sudah, Ayah tak akan bisa mengerti. Mama, Ia hanya diam tak peduli. Tak ingin berlama-lama, aku memutuskan berangkat saja.
“ aku berangkat sekolah dulu, Yah, Mah,” ucapku seraya menyalimi tangan Ayah dan Mama. Respon mereka hanya diam, aku sudah biasa seperti itu. Jadi, tak masalah bagiku.
Saat sedang berjalan ke rumah Faida, aku bertemu dengan ibu Nani. Setiap akan berangkat, aku memang mesti ke rumah Faida untuk berangkat bersama.
“ sekolah, Nin.” Tanya ibu Nani.
“ iya, habis dari mana, Bu?” jawabku diiringi senyum.
“ habis dari warung. Oh, ya, Nin, kamu belum bisa bawa motor? Buat yang dulu lupain aja, latihan lagi. Malu tuh sama Faida. Masa, iya, kamu kalah sama dia.”
Jlebb! Ini sebenarnya semangat atau sindiran? Menyesakkan sekali. Dimana mana hal itu selalu dipertanyakan kepadaku. Sesekali tolong! Aku ingin bisa berdamai dengan masa lalu. Akhh!
Aku berjalan santai, pikiranku berkecamuk. Aku inscure, aku tak bisa mereka yang bisa kesana kemari seenak mereka. Sedangkan aku? Ah sudahlah.
Sampai di sekolah. Aku dan Faida berpisah. Aku kelas delapan C, Faida delapan A. Dalam perihal kelas saja, aku kalah lagi oleh Faida. Tak ada yang istimewah dariku, aku hanya poerempuan biasa yang sering mendapatkan sindiran.
“Nin, aku duluan, ya,” ucap Faida.
“iya, Da, hati hati,” jawabku seraya tersenyum.
“oh ya, nanti aku ada ekskul. Kamu pulangnya, gimana?” bahuku merosot. Aku juga bingung pulangnya bagaimana. Menit berikutnya aku tersenyum.
“oh gitu. Ga pa-pa, aku bisa jalan kaki,” jawabku dengan tawa renyah.
“hah, yang bener? Jaraknya kan jauh, Nin.”
“ ha ha, gak pa-pa. Sekalian olahraga.” Tawaku lagi, ah sebenarnya di hati aku jugagelisah pasalnya belum pernah pulang jalan kaki. Namun, bagaimana lagi.
“Oke, aku ke kelas duluan, ya,” ucap Faida melambaikan tangan sambil berjalan. Aku balas melambaikan tangan. Yuk, bisa, yuk! Batinku menyematkan diri. Sesampainya di kelas, aku bertemu dengan Nilam—sahabatku.
“Hai, Nin! Sama Faida lagi? Oke, kuatkan mental lagi. Apakah tak ada pertanyaan lain selain itu? Pikirku. Aku muak sekali.
“Iya, he he,” jawabku beruusaha santai seraya berjalan menuju bangku, di samping Nilam.
“Oh, gitu, aku mau ngomong sesuatu, boleh?” ujar Nilam. Aku menautkan alis. Tumben sekali Nizam izin dulu, biasanya juga tidak.
Aku coba tertawa ringan, “Boleh kok, ngomong apa?
“Coba kamu latihan lagi, semakin ke sini, kamu itu semakin besar. Apa iya kamu nggak butuh keluar rumah buat pergaulan atau urusan? Aku yakin kamu bisa kok.” Sudah kuduga, Nilam akan mengatakan itu lagi. Aku muak. Bukannya tak menghargai, tapi jujur aku masih sensitif akan hal itu. Tak tahukah Nilam, bahwa berdamai dengan kejadian itu sungguh sulit, ah semua orang sama saja. Menyebalkan.
“Nggak semudah itu, Nilam. Kamu kenapa nggak nisa ngertiin, aku? Sanggahku.
“Bukannya aku nggak mau ngertiin, tapi aku juga nggak mau kaya gini terus. Terpaku sama masa lalu, itu Cuma bisa bunuh mentalmu secara perlahan.” Aku mengangguk, tak mau berlarut-larut akan topik ini.
“Iya, makasih. Aku pikirin lagi,” responku. Ini tak main-main. Aku akan coba memikirkan hal itu lagi. Meski ... berat.
Pulang sekolah. Aku sedang berjalan sambil mendengarkan musik menggunakan geadset bluetoth. Saat aku sedang menikmati alunan musik sambil berjalan, kenal saja tidak, mungkin dia ada urusan lain, bukan denganku, pikirku. Akan tetapi ....
“Nindi!” Ini bukumu, kan? Aku menoleh. Ah iya benar, itu buku yang sedang kucari tadi, tetapi tidak ketemu. Ternyata ....
Tunggu , kenapa dia tahu namaku? “Eh iya, kok bisa sama kamu?” tanyaku canggung.
“Tadi jatuh di gerbang.”
“O ... oh, iya, tahu namaku dari?” tanyaku lagi.
“Ha ha, aneh kamu. Kita kan seangkatan, aku kelas delapan B,” jawab lelaki itu tertawa. Adakah yang lucu?
“Oh gitu. Makasih ya,” ucapku seraya mngambil buku tersebut.
“Sama-sama, krnalin namaku, Fadhil.” Dia mengulurkan tangannya.
“Eh iya, sendirian aja? Temanmu ke mana?” Aku bingung menjawab apa.
“Lagi ekskul, heh ....”
“Belum bisa,” jawabku seadanya. Tanpa sadar caioran bening keluar. Menyebalkan sekali, tak bisa di ajak kompromi. mata. Meski Fadhil menanyakan perihal air mata itu, aku pilih menghindar. Fadhil mengajakku pulang bersama, setelah berpikir cukup lama, aku iyakan ajakannya.
Di perjalanan, Fadhil mrngurai diam dengan mengajakku berbicara. “Nin, menurutmu kekurangan emang sesuatu hal yang harus selalu dibicarain?”
Eh kok kaya ngena.
“Setiap orang punya kekuranan dan kelebihan. Namun, sayangnya banyak orang yang sulit menerima kekurangan yang dimiliki. Seperti aku, contohnya, heh.” Aduh keceplosan.
“Kamu kenapa, emang?” tanya Fadhil. Aku agak risih, tapi ada rasa ingin menumpahkan apa yang selama ini dipendam.
“Ya gitu, aku pengen kayak orang lain. Rasanya selalu dibandingkan sama orang lain itu nggak enak, apalagi perihal kekurangan. Aada juga yang bilang nggak boleh di situ terus, tapi apa iya mereka ngasih omongan, tapi mereka nggak bantu. Mereka lebih ngerasain, gimana rasanya insecure karena kelebihan orang lain, dan banyak orang memaksa buat jadi seperti orang lain? Padahal itu bagian dari kekurangan kita. Dipaksa berdamai dengan masa lalu, luka dan dipaksa sempurna.”
Terlalu panjang aku bicara, aku tersenyum tipis. Hati Fadhil terenyuh. Fadhil terlihat tak menjawab pertanyaanku, tetapi sepertinya dia tahu seberapa sakitnya, dipaksa sempurna. Apa mungkin, karena Fadhil juga pernah mengalaminya?
“Aku nggak tahu mau jawab apa. Tapi, aku mau kasih tahu kamu satu hal. Jadilah diri sendiri. Kamu hidup bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk ada dan nyata. Kamu hidup bukan untuk dihargai orang lain, tapi kamu hidup untuk menghargai dirimu sendiri. Kekurangan bukanlah patokan untuk selalu dihina, untuk disempurnakan. Mulai sekarang, jadilah dirimu sendiri. Jangan insecure, minder, sedih atas kekurangan yang kamu miliki. Yuk bisa, yuk! Semangat,!” Fadhil tersenyum manis.